Kebudayaan pada Masa Penjajahan
Kebudayaan pada Masa Penjajahan – Masuknya pengaruh asing ke Indonesia membawa dampak yang besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dampak masuknya pengaruh itu bisa dilihat dari sisi negatif dan positif. Fakta sejarah menyebutkan bahwa kita telah dieksploitasi sehingga kita hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kamu bisa menyebutkan bagaimana para penjajah memperlakukan bangsa Indonesia dan mengeruk kekayaan alamnya.
Meskipun begitu, kita juga melihat bagaimana bangsa-bangsa asing itu memperkenalkan beragam pengetahuan dan kebudayaan kepada kita. Setidaknya kita bisa menyebut dua model kebudayaannyang datang pada periode itu ke Indonesia yaitu kebudayaan Barat yang dibawa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris serta kebudayaan Timur yang dibawa Jepang. Jauh sebelum bangsa Barat datang membawa kebudayaan ke Indonesia, kita telah memiliki kebudayaan yang tinggi dan termasyhur. Kebudayaan itu berasal dari pengaruh Hindu–Buddha yang datang dari India dan kebudayaan Islam yang datang dari Arab. Kamu tentu bisa menyebutkan dengan mudah apa saja contoh kebudayaan dari kedua periode tersebut.
Setelah bangsa Barat datang, kebudayaan Indonesia semakin beragam. Kebudayaan Portugis yang masih tersisa hingga kini antara lain dalam pemberian nama orang seperti de Pereira, de Fretes, nama hari seperti Minggu yang berasal dari kata ”San Domingo”, dan kesenian keroncong Morisco.
Kebudayaan Barat lain yang datang ke Indonesia adalah berasal dari Belanda. Lamanya masa penjajahan Belanda dan efektifnya kekuasaan kolonial di Indonesia menyebabkan kebudayaan Barat bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kebahasaan dan kesusastraan.
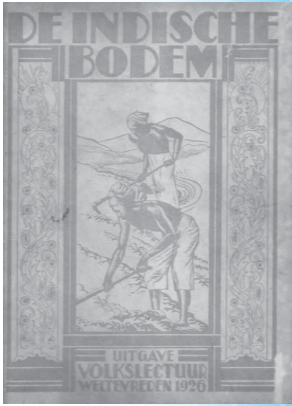
Perkembangan Bahasa dan Sastra pada Masa Kolonial Barat
Kolonialisme yang dikembangkan Belanda banyak melahirkan masyarakat baru yang bercirikan masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota antara lain bergerak di bidang jasa dan perdagangan beserta dengan prasarana dan infrastrukturnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai, pemerintah kolonial juga mendirikan banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa perantara bahasa Belanda. Interaksi dan integrasi warga pada masyarakat kolonial pun tidak bisa dihindarkan. Apalagi didukung dengan industri penerbitan khususnya persuratkabaran.
Sistem surat kabar telah dimulai sejak zaman permukiman orang Belanda di Batavia tahun 1659 dan mencapai puncak pada masa kapitalisme mendominasi Hindia Belanda. Surat kabar yang pertama adalah Bataviasch Courant yang terbit secara terbatas untuk permukiman elite Belanda di Batavia. Selanjutnya, industri penerbitan berkembang pesat seiring munculnya banyak masyarakat perkotaan dan berdampak pada perkembangan bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan nasionalisme. Banyak para sastrawan Indonesia yang menuangkan gagasan dan idenya ke dalam beragam media terbitan. Tulang punggung berkembangnya kebudayaan Belanda di Indonesia adalah digunakannya bahasa Belanda. Bahasa ini semula hanya digunakan secara elite dan terbatas pada masyarakat Belanda dan keturunannya saja sejak zaman VOC. Pada tahun 1778, berdiri perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan ini banyak bergerak di bidang koleksi naskah dan karya tulis tentang budaya dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Lalu, pada tahun 1839, berdiri percetakan buku yang dipelopori oleh Cijveer & Company. Percetakan ini berubah nama menjadi Cijveer & Knollaert. Dengan menggunakan penerbitan pulalah para misionaris dan zending menyebarluaskan agama Kristen, antara lain melalui pembuatan Alkitab dan beragam bentuk pamflet. Orang-orang Eropa dan Cina peranakan juga terlibat di dalam perkembangan bahasa dan sastra pada masa kolonial. Pada akhir abad XIX, mereka mendirikan penerbitan dan percetakan yang menghasilkan sekitar 3.000 judul buku, pamflet, dan terbitan lainnya dalam bahasa Melayu Tionghoa atau Melayu pasar. Mulai abad XX, dunia penerbitan dan percetakan digunakan oleh para tokoh pergerakan untuk menuangkan ide dan gagasannya tentang nasionalisme. Tokoh itu antara lain R.M.A.A. Kusumo Utojo, Pangeran Achmad Djajadiningrat, PAA. Kusumojudo, R.M. Sutomo, dan R.A.A. Tirtokusumo. Kecenderungan ini menyebabkan pemerintah pada tanggal 14 September 1908 membentuk Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur yang diketuai oleh G.A.J. Hazeu. Melalui komisi ini berkembang beragam bentuk karya sastra. Penerbitan berbagai buku cerita melalui komisi tersebut dimulai tahun 1910 misalnya buku Dongeng Tjarijosipoen Tijang Sepoeh. Pengarang C.M. Pleyte tahun 1911, menulis Pariboga Salawe Dongeng Soenda dalam bahasa Sunda. Buku-buku lain dalam bahasa Melayu ditulis oleh R.M. Tirto Adi Soerjo yang menulis Njai Permana tahun 1912, Si Bedjo Joernalis Berontak dan Student Hidjo yang ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo tahun 1919, dan Semaun yang menulis Hikajat Kadiroen tahun 1924. Kebanyakan tema yang ditulis adalah percintaan, kawin paksa dan politik sosialis. Selain buku-buku tersebut, masih banyak karya sastra yang termuat di dalam beragam surat kabar.
Pada tahun 1917 Komisi Bacaan Rakyat berubah namanya menjadi Balai Pustaka, namun tetap memperlakukan sensor yang ketat terhadap naskah yang akan diterbitkan. Salah satu bentuk sensor itu antara lain didasarkan pada Nota Rinkes yang intinya melarang karya sastra bermuatan politik apalagi antipemerintah, menyinggung adat dan melanggar susila. Meskipun begitu, para pengarang dan sastrawan Indonesia tidak pernah menyurutkan sikapnya untuk berpikir kritis. Justru pada periode ini lahir pengarang-pengarang besar dan sastrawan besar kita. Mereka antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Sanusi Pane. Karya sastra yang lahir antara lain Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Salah Asuhan karya Abdul Muis, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana, dan Atheis karya Achdiat Kartamihardja. Pada perkembangan selanjutnya, karya sastra yang muncul sudah banyak diwarnai oleh pemikiran pergerakan nasional meskipun secara samar dan dibungkus dalam beragam simbolisasi. Karya sastra pada periode Balai Pustaka juga ada yang berbentuk puisi atau sajak. Kerangka berpikir sastrawannya melingkupi karya sastranya. Pada saat itu, pengertian nasionalisme belum muncul dan sastrawannya masih tergantung pada etnisitasnya. Misalnya karya Muh. Yamin pada tahun 1921 yang berjudul Bahasa, Bangsa berikut ini (Ajip Rosidi, 1969: 20).
Selagi kecil berusia muda
Tidur si anak di pangkuan bunda
Ibu bernyanyi, lagu dan dendang
Memuji si anak banyaknya sedang
Berbuai sayang malam dan siang
Buaian tergantung di tanah moyang
Terlahir di bangsa, berbahasa sendiri
Diapit keluarga kanan dan kiri
Besar budiman di tanah Melayu
Berduka suka, sertakan rayu
Perasaan serikat menjadi padu
Dalam bahasanya permai merdu
Meratap menangis bersuka raya
Dalam bahagia bala dan baya
Bernafas kita pemanjangkan nyawa
Dalam bahasa sambungan jiwa
Di mana Sumatra di situ bangsa
Di mana Perca di sana bahasa
Andalasku sayang jana bejana
Sejakkan kecil muda teruna
Sampai mati berkalang tanah
Lupa ke bahasa tidak kan pernah
Ingat Pemuda, Sumatra malang
Tiada bahasa, bangsa pun hilang
Muh. Yamin memerlukan waktu delapan tahun untuk mempunyai kesadaran tentang nasionalisme Indonesia. Karena, karya-karyanya delapan tahun kemudian telah menunjukkan kesadaran tanah airnya bukan Sumatra (Andalas) tetapi Indonesia dan bahasa Melayu bukan hanya milik bangsa Sumatra. Kesadaran inilah yang mewarnai munculnya era pergerakan nasional. Pada masa ini, kombinasi antara sastra dan nasionalisme sangat mewarnai karya sastra yang muncul. Bahasa Indonesia mendapat dorongan kuat setelah seluruh elemen pergerakan nasional mencapai kesepakatan untuk menemukan identitas nasional dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan sastra Indonesia berkembang semakin cepat. Pada bulan Juli tahun 1930, para pemikir Sumpah Pemuda menerbitkan majalah Pujangga Baru. Majalah ini digunakan sebagai media pendorong dinamika dan mengungkapkan citra keagungan kebudayaan Indonesia. Tokoh utama majalah ini antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, Armyn Pane, Amir Hamzah, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantoro, dan Hoessein Djajadiningrat. Bahkan melalui media ini, kita bisa membaca perdebatan para pemikir bangsa mengenai kebudayaan Indonesia, yang dikenal dengan Polemik Kebudayaan. Perjuangan untuk menempatkan bahasa Indonesia secara terhormat juga pernah dilakukan oleh M.H. Thamrin (Fraksi Nasional Volksraad) tanggal 12 Juli 1938. Karya sastra yang muncul pada periode ini antara lain Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana dan lakon Sandyakala ning Majapahit karya Sanusi Pane. Karya lain berupa sajak, seperti contoh sajak Nasib Tanah Airku karya Asmara Hadi.
Perkembangan Bahasa dan Sastra pada Masa Pendudukan Jepang
Perkembangan kebudayaan masyarakat di Nusantara pada masa pendudukan Jepang banyak diwarnai oleh dua kutub kepentingan. Di satu sisi Jepang berkeinginan untuk bisa memobilisasi rakyat demi kepentingan perangnya, di sisi yang lain perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah sampai pada tingkat yang matang. Kedatangan bala tentara Jepang memang sudah lama ditunggu oleh rakyat terutama masyarakat Jawa. Hal ini karena beredarnya ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa kemerdekaan rakyat akan tercapai bila telah datang orang-orang yang bertubuh kerdil, berkulit kuning dari utara dan lamanya seumur jagung. Nuansa itulah yang mendominasi perkembangan kebudayaan pada masa Jepang. Politik bahasa yang dikembangkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dimulai dengan melarang segala pemakaian bahasa Belanda. Tujuannya adalah untuk menampilkan kesan negatif kebudayaan Barat di mata rakyat, sehingga rakyat antipati terhadap Belanda. Dampaknya adalah penggunaan bahasa Indonesia semakin luas di kalangan rakyat karena bahasa Jepang belum banyak diketahui rakyat. Hal ini tentu berlawanan dengan politik kolonial Belanda yang melarang segala yang berbau Indonesia.
Pada tanggal 20 Oktober 1943, Kantor Pengajaran Jepang di Jawa mendirikan sebuah komisi untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Komisi ini selain didukung oleh tokohtokoh sastrawan juga terdiri atas politisi terkemuka seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan Ki Hajar Dewantoro.
Komisi ini berhasil menentukan 7.000 istilah dan mengganti nama-nama kota peninggalan Belanda seperti Batavia menjadi Jakarta, Mr. Cornelis (Jatinegara), dan Buitenzorg (Bogor). Karya berupa sajak pada periode ini bisa dibaca dari karya Rosihan Anwar yang berjudul Kisah di Waktu Pagi berikut ini (H.B. Jassin, 1967: 155).
Seperti perjurit memeras daya
Pagi dan senja tiada beda
Senantiasa berjalan di lebuh raya
Bertujuan nyata hingga saatnya
Bangsa bersemayam di Puncak nan Jaya
Akupun ingin seperti mereka
Di lapang kerjaku berbaktikan daya
Guna kemenangan segala kita
Berkobarnya Perang Pasifik juga mengilhami sastrawan kita untuk membuat karya sastra. Misalnya roman Taufan di Atas Asia karya El Hakim. Karya sastra pada masa Jepang memiliki peran yang besar di dalam menggelorakan semangat bangsa untuk meraih kemerdekaan.[pi]




